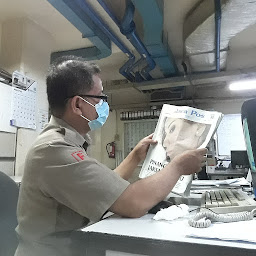MINGGU, pagi-pagi buta, istri saya bertanya, "Mobil yang parkir di depan pagar rumah kita itu punya siapa?"
"Mobil apa?"
"Avanza hitam."
Demi memastikan, saya keluar rumah. Membuka pagar, dan mendapati mobil sejuta umat itu anggun sekali. Parkir manis di depan pagar. Oh, rupanya tetangga sebelah jadi beli mobil...
Panggilan sholat subuh sudah seperempat jam yang lalu bersautan, tapi panggilan perut yang barusan saya rasakan, langsung membuat langkah kaki saya mak jranthal menuju 'belakang'. Saya bablas, buang hajat.
Perut saya mulas hebat. Juga begah. Wah, wah, wah. Kalau sudah begini, alamat sakit maag saya kambuh. Padahal, saya makan juga tidak telat. Makan pedas, tidak. Makan yang asem-asem juga tidak, lalu tersangkanya siapa dong?
Oh, jangan-jangan....
Sabtu pagi kemarin, ada penjual bubur ketan hitam lewat. Tiap pagi sih ibu itu jualan lewat depan rumah saya. Tetapi saat itu, saya yang sedang jalan pagi, dan sedang bawa HP, punya ide lain. Apa lagi kalau bukan buat konten😊
Ceritanya saya sedang iseng baru bikin channel Youtube. Kanal baru saya ini niche-nya kuliner. Wabil khusus kuliner kelas kaki lima. Dan sudah beberapa video saya unggah, traffic-nya lumayan; salah satu video ditonton banyak viewers dengan sebagian besar mampir atas rekomendasi Youtube.. Nah, boleh juga nih si penjual bubur ketan hitam itu saya bikin bahan konten.
Singkat cerita, sejak saya membeli sampai makan bubur ketan hitam itu saya syuting. Saya makan lahap. Tak lupa makannya sambil bicara dan kicipak lidah dalam mengunyah saya niru gayanya Dede Inoen yang punya narasi khas: cantek sekaleee itu.
Karena merasa dengan sarapan ketan hitam itu perut saya kenyang, makan makan berikutnya tentu agak siang. Toh, lambung sudah terisi ketan hitam.
Nah itu dia suspect-nya. Kambing hitamnya. Ketan hitamlah yang bikin perut saya mulas, sakit. Karena konon, kata orang-orang, bila belum sarapan nasi tetapi perut sudah diisi ketan, bagi yang punya penyakit gangguan lambung, maag-nya bakalan kambuh. Tetapi masalahnya, saya dapat info ini belakangan.
Tetapi tunggu dulu, sakit perut dan berlanjut kepada badan panas-dingin dan meriang ini, adalah juga dipicu oleh tetangga sebelah rumah saya yang beli Avanza hitam.😇****