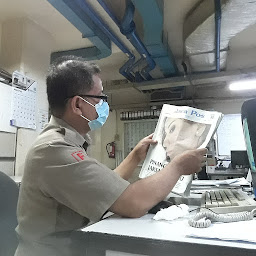KANG KARIB, ketika masih kecil, saat sandal jepitnya putus dan bilang ke orang tuanya, cerita selanjutnya sungguhlah lumrah. Tepatnya lumrah dan normal di zaman itu. Yakni, bukan lalu dibelikan sandal jepit baru, namun dicarikan peniti atau paku. Lalu ditusukkanlah paku atau peniti itu ke bagian
srampat sandalnya yang putus. Beres. Sandal bisa dipakai lagi.
"Itu
lak zaman
doeloe, Kang", Mas Bendo mengomentari cerita itu. "Coba anak sekarang, mana mau mereka pakai sandal jepit 'berpenangkal petir' begitu".
"Begitulah, nDo. Setiap zaman mengandung kelumrahannya sendiri".
Lalu Kang Karib menukil contoh termutakhir. Akibat
Covid-19
. Yang orang dianjurkan untuk jangan salaman dulu. Selalu pakai masker. Tentu saja ada yang
manut, ada yang
ngeyel. Lazim. Namanya juga
homo sapiens. Nah, sampai kapan harus begitu? Harus jangan salaman, harus selalu bermasker?
Para orang pintar pun belum tahu kapan
pageblug ini akan
game over. Kapan pandemi ini berakhir. Nah, jangan-jangan orang kemudian keterusan tidak suka salaman dan kemana-mana dengan penutup mulut.
"
Lha lak tambah bagus
to, Kang", sahut Mas Bendo. "Orang menjadi makin sadar jaga kesehatan".
"Itu
lak kalau maskeran, nDo. Maksudku kalau keterusan tidak mau salaman
piye?".
"Aku juga lagi mikir, Kang."
"Mikir
opo?"
"Mikir konsep rumah", jawab Mas Bendo. "Rumahku
kan kamar mandinya di belakang. Di dekat dapur".
"Lho
lak normalnya memang
gitu kan, nDo?" sela Kang Karib.
"Itu
lak normal cara lama, Kang. Kalau normal gaya baru, yang dibilang orang dengan kata 'keminggris'
New Normal itu, bisa beda, Kang."
"Beda
piye jal?"
"Sekarang orang kalau dari keluar rumah, dari berbelanja atau pulang bekerja, kan harus bebersih badan dulu. Mandi, ganti baju, baru boleh bercengkerama dengan orang rumah.
Lha kalau kamar mandinya di belakang,
lak sudah kadung masuk rumah, penyakit bisa keburu ngikut masuk".
"Jadi?"
"Menurut ramalanku, selain harus selalu menerapkan segala protokol kesehatan yang sekarang umum dikampanyekan, di rumah-rumah,
jedhing atau kamar mandi, nantinya tempatnya tidak 'disembunyikan' di belakang seperti selingkuhan. Tapi di depan, di dekat halaman".****